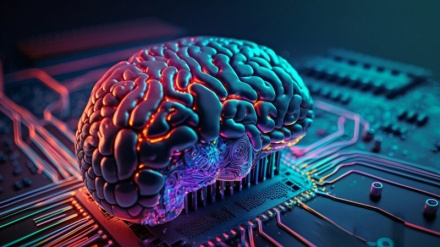Ketika Mesin Mengungguli Akal Empiris, Apa yang Masih Tersisa bagi Manusia?
Oleh: Khusnul Yaqin, Guru Besar Ekotoksikologi Perairan, Universitas Hasanuddin
Hari ini saya membaca berita bahwa Elon Musk yang starlinknya dihajar Republik Islam Iran membuat prediksi yang mengkhawatirkan tentang nasib manusia dihadapan mesin kecerdasan buatan (AI).
Elon Musk memperingatkan bahwa dalam sekitar empat tahun ke depan gelar sarjana dan berbagai kualifikasi formal akan makin kehilangan daya tawarnya, karena laju pembelajaran AI berkembang secara eksponensial dan sanggup mengakses serta mensintesis pengetahuan manusia hampir seketika; bahkan keterampilan yang diasah manusia selama satu dekade bisa segera tertinggal dibanding kemampuan AI yang “belajar” dalam hitungan detik, sementara pengalaman kerja 20–30 tahun pun tergerus ketika mesin dapat menyalin, membagikan, dan mengoptimalkan pengalaman secara global; dalam skenario itu, keunggulan berbasis senioritas atau keahlian yang repetitif dinilai tidak lagi kokoh, uang pun dipertanyakan perannya bila AI dan robot menekan biaya produksi barang dan jasa mendekati nol, sehingga nilai inti manusia bergeser dari sertifikat dan kekayaan menuju kemampuan beradaptasi dan berinovasi.
Masalahnya, bagaimana kampus atau lembaga pendidikan melahirkan manusia inovatif jika inovasi yang diajarkan masih bergerak di dalam batas rasionalitas empiris, wilayah yang dapat dipetakan, dipercepat, bahkan dilampaui oleh AI?
Di hadapan kecerdasan buatan (AI), kita kerap tergoda untuk mengukur manusia hanya dengan alat ukur yang disukai mesin: data yang terstruktur, pola yang terhitung, dan rasionalitas empiris yang dapat diduplikasi. Tetapi ada satu wilayah yang sejak awal memang tidak dirancang untuk dijangkau algoritma: data khayal ruhani—bukan “khayalan” dalam arti fantasi liar, melainkan daya imajinasi kreatif yang dalam tradisi tasawuf-falsafi dipahami sebagai organ pengetahuan yang menjembatani yang gaib dan yang tampak.
Dalam kerangka Ibn ‘Arabi, realitas bertingkat—dan pengetahuan manusia tidak berhenti pada apa yang ditangkap indera. Pada horizon tertinggi, wahidiyah (sering dipahami sebagai ranah penampakan Nama-Nama Ilahi) memuat a‘yan tsabitah: “entitas tetap” atau arketipe-arketipe ilmu Ilahi yang menjadi kemungkinan-kemungkinan wujud sebelum tampil sebagai kenyataan di alam ciptaan empiris. Ini bukan benda-benda di luar sana, melainkan “pola-pola kemungkinan” yang terhimpun dalam pengetahuan Tuhan. Tradisi kajian Ibn ‘Arabi memang menempatkan a‘yan tsabitah sebagai konsep sentral dalam ontologinya.
Di bawah horizon a‘yan tsabitah itu, Ibn ‘Arabi dan para penerus tradisi hikmah-‘irfan menempatkan ‘alam al-khayal—dunia imajinal (mundus imaginalis): sebuah wilayah perantara (barzakh) yang bukan semata-mata materi, namun juga bukan abstraksi rasional murni. Henry Corbin menegaskan dunia imajinal sebagai “interworld” (barzakh) yang memiliki objektivitasnya sendiri: bukan sekadar “khayalan psikologis”, tetapi medan bentuk-bentuk halus tempat makna ruhani mengambil rupa yang dapat “dsaksikan” oleh kesadaran yang disucikan.
Di sinilah relevansi pembedaan AI dan mamusia: daya khayal ruhani berada lebih tinggi—lebih “dekat” ke wilayah makna yang bersumber dari pengetahuan Ilahi—daripada daya khayal barzakhi yang masih bertaut kuat dengan rasionalitas alam materi.
Daya khayal barzakhi dapat menghasilkan citra, analogi, dan penalaran kreatif, tetapi masih berputar di orbit pengalaman empiris (menganalogikan, menggabungkan, menyusun ulang). Sementara daya khayal ruhani bukan sekadar “mengolah” data; ia “menerima” penyingkapan intensional ruhani—dengan syarat batin disiapkan.
Dengan kata lain, ia adalah epistemologi yang mengandaikan tazkiyah (penyucian), adab, dan disiplin ruhani, bukan sekadar kapasitas kognitif.
AI, dalam definisinya hari ini, hanya bertanding di ranah rasionalitas empiris dan turunannya: statistik, probabilitas, optimasi, sintesis teks, dan pemodelan pola. Ia bisa melampaui manusia biasa dalam kecepatan, memori, dan keluasan akses serta inovasi yang bekerja di rana rasionalutas empiris. Tetapi tetap saja ia bekerja di dalam dunia yang dapat direpresentasikan: simbol, token, parameter. Dunia khayal ruhani tidak tunduk pada representasi semacam itu, sebab ia menuntut transformasi subjek yang mengetahui—bukan hanya perbaikan alat.Karena itu, masalah besar pendidikan tinggi bukanlah “AI akan menggantikan kampus”, melainkan kampus yang selama ini terlalu bangga menjadi pabrik rasionalitas empiris belaka. Kita melatih mahasiswa menjadi operator pengetahuan, bukan penembus batas kreativitas ilahiyah. Kita membiasakan mereka menjadi konsumen metode, bukan penemu horizon berpikir kritis ternascenden. Lalu ketika AI datang sebagai “operator” yang lebih cepat, kita panik: seolah-olah manusia tak punya wilayah keunggulan lagi.
Padahal sejarah ilmu menunjukkan: lompatan-lompatan besar sering lahir bukan dari “komputasi yang rajin”, melainkan dari intuisi kreatif yang melampaui kebiasaan. Di titik ini, kisah Srinivasa Ramanujan menjadi cermin yang memalukan bagi pendidikan modern: seorang pemuda desa di India yang sebagian besar belajar matematika secara mandiri, menulis hasil-hasilnya dalam kesendirian, lalu pada 1913 mengirim surat kepada G.H. Hardy di Cambridge; Hardy terkejut karena di dalamnya terkandung teorema dan identitas yang “asing” namun brilian, lalu mengundangnya ke Inggris.
Ramanujan kemudian bekerja di Cambridge, meraih gelar dan pengakuan ilmiah dengan ratusan teori matematika, dan pada 1918 terpilih sebagai Fellow of the Royal Society serta Fellow of Trinity College, Cambridge—pencapaian luar biasa bagi seseorang yang “hampir tanpa pelatihan formal empiris” dalam matematika murni.
Yang perlu ditekankan: Ramanujan bukan sekadar “orang jenius yang kebetulan”. Ia adalah contoh bahwa kreativitas ilmiah yang sering tumbuh dari suatu ruang batin: ketekunan yang nyaris asketik, keheningan yang panjang dalam tempat ibadah, serta intuisi yang berani—sebuah “cara mengetahui” yang tidak selalu bisa diajarkan lewat modul dan rubrik penilaian. Pendidikan modern sering menutup pintu terhadap cara mengetahui ini karena takut dianggap tidak ilmiah. Namun kita lupa: “ilmiah” bukan berarti miskin ruh; ilmiah berarti jujur pada realitas dengan berbagai tingkatannya. Jika realitas bertingkat, maka ilmu yang hanya mengakui satu tingkat adalah reduksionisme, bukan sains.
Lalu bagaimana kampus bergerak? Di sini Mulla Sadra menawarkan jalan yang, jika diterjemahkan dengan cerdas, bisa menjadi kerangka pembaruan pendidikan: al-asfār al-arba‘ah, empat perjalanan ruhani-intelektual. Dalam tradisi Sadra, perjalanan bukan wisata spiritual; ia adalah metodologi transformasi wujud subjek pengetahuan.Pertama, perjalanan dari makhluk menuju Tuhan (min al-khalq ila al-Haqq): tahap berangkat dari pengalaman dunia, menembus tirai kebiasaan, menata ulang pertanyaan paling dasar tentang wujud, sebab, dan intensi ilahiyah. Ini adalah fase “pembersihan epistemik”: menyingkirkan kepastian palsu dan memulai pencarian yang serius.
Kedua, perjalanan di dalam Tuhan bersama Tuhan (fi al-Haqq bi al-Haqq): fase kontemplasi mendalam atas realitas Ilahi—sifat-sifat, nama-nama, dan keterarahan batin yang membuat subjek “terserap” oleh yang dicari. Dalam bahasa Sadra, ini berkaitan dengan kefanaan ego pengetahuan (efasemen diri) dan pemurnian niat; bukan sekadar belajar konsep “ketuhanan”, melainkan mengalami keteraturan makna yang memancar dari-Nya.
Ketiga, perjalanan dari Tuhan menuju alam bersama Tuhan (min al-Haqq ila al-khalq bi al-Haqq): fase kembali membaca dunia—alam, waktu, penciptaan, hubungan Tuhan-dunia—dengan mata yang telah dibentuk oleh kedalaman ruhani. Di sini sains mendapatkan tempatnya yang wajar: bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai tafsir atas ayat-ayat kauniyah untuk memproduksi inovasi-inovasi yang tak terjangkau oleh AI.
Keempat, perjalanan di dalam alam bersama Tuhan (fi al-khalq bi al-Haqq): fase pengabdian kreatif—masuk ke masyarakat, ilmu, dan sejarah dengan membawa “kehadiran” (presence) intensional ilahiyah. Ini wilayah etika dan tanggung jawab: bagaimana pengetahuan melahirkan keadilan, membimbing kebijakan, memuliakan kehidupan, dan mencegah kerusakan.
Jika empat perjalanan ini diterjemahkan ke dalam desain kampus, maka reformasi pendidikan tidak berhenti pada “mengajari AI” atau “mengganti kurikulum”. Kita perlu mengubah orientasi: dari sekadar kompetensi menuju transformasi; dari “output cepat” menuju kedalaman; dari rasionalitas empiris semata menuju integrasi akal, khayal, dan ruh.Secara praktis, kampus dapat membangun tiga lapis pembelajaran. Lapis pertama tetap rasional-empiris: metodologi, data, laboratorium, dan literasi AI. Lapis kedua adalah barzakhi: pelatihan imajinasi ilmiah—model konseptual, metafora, visualisasi matematis, penalaran analogis, dan kemampuan merumuskan masalah secara kreatif (problem finding, bukan hanya problem solving). Lapis ketiga adalah ruhani: disiplin adab ilmu, tazkiyah, keheningan terarah, pembiasaan tafakkur, dan latihan mengikat ilmu pada tujuan etik dan spiritual. Di lapis ketiga ini, kampus tidak berubah menjadi “pesantren ritual”, tetapi menjadi institusi yang tahu bahwa pengetahuan tanpa penyucian mudah menjadi instrumen empirisis yang mudah dilibas Ai.
AI akan terus menang dalam lomba kecepatan dan keluasan informasi empiris. Itu bukan tragedi. Tragedi terjadi jika kampus dan lembaga pendidikan ynag lain menyerah dan ikut menilai manusia hanya dengan ukuran yang disukai mesin. Pendidikan tinggi, jika ingin melahirkan “Ramanujan-Ramanujan baru”, harus berani memulihkan wilayah yang tak dapat diotomasi: daya khayal yang kreatif dan daya ruhani yang menyinari akal. Pada titik itu, universitas tidak lagi bersaing dengan AI pada medan yang bukan miliknya, melainkan menegakkan kembali martabat manusia sebagai subjek pengetahuan, yang bukan hanya menghitung, tetapi juga menyaksikan dan mengalami spiritual disclosure.