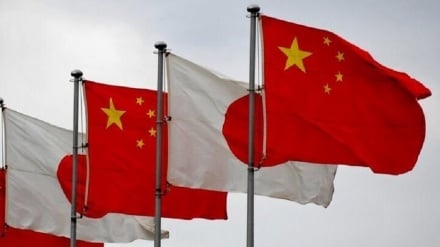Tantangan Takaichi, Perdana Menteri Perempuan Pertama Jepang
Sanae Takaichi, politisi keras kepala dan sayap kanan, dengan naik ke jabatan perdana menteri, mencatat namanya sebagai perempuan pertama di puncak pemerintahan Jepang.
Jepang, negara yang selama beberapa dekade diperintah oleh laki-laki konservatif, pada hari Selasa (21 Oktober) menyaksikan sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sanae Takaichi, salah satu rekan dekat mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, dengan memperoleh 237 suara dari 465 suara di Majelis Rendah, terpilih sebagai perdana menteri.
Meskipun pada pandangan pertama momen ini tampak seperti pemecahan “plafon kaca” bagi perempuan, para analis dan pengamat politik memperingatkan bahwa pemilihan ini, lebih dari apa pun, menunjukkan pendalaman dan percepatan pergerakan Jepang ke arah kanan ekstrem dan kembali pada nilai-nilai masa lalu yang kontroversial.
Dalam paket berita Pars Today ini, perkembangan Jepang dengan naiknya perdana menteri perempuan pertama di negara tersebut dibahas sebagai berikut:
Koalisi rapuh di atas gunung berapi politik
Setelah berminggu-minggu ketegangan politik dan runtuhnya koalisi yang berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP) yang dipimpin oleh Takaichi, untuk mempertahankan kekuasaan, membentuk koalisi dengan partai sayap kanan Nippon Ishin no Kai (Partai Inovasi Jepang). Koalisi ini, yang lebih menyerupai kesepakatan strategis untuk bertahan hidup, sejak awal telah menghadapi banyak ketidakjelasan.
Partai Ishin, yang dulunya muncul dengan slogan “anti korupsi” dan “anti Partai Demokrat Liberal”, kini berdiri di sisi partai tersebut, tetapi tidak memiliki kursi di kabinet. Janji utama pemerintahan baru ini adalah penurunan pajak bahan bakar guna mengurangi tekanan ekonomi terhadap rumah tangga, namun banyak tuntutan neoliberal ketat Partai Ishin — seperti pengurangan layanan sosial dan anggaran kesehatan — ditunda ke masa depan.
Perempuan Besi baru; pewaris Abe dan Thatcher
Sanae Takaichi, berusia 63 tahun, yang merupakan pengagum berat “Margaret Thatcher”, mantan perdana menteri Inggris yang otoriter, dalam wacana politiknya menekankan pemulihan “kehormatan nasional” dan pembangunan “Jepang yang lebih kuat dan lebih mandiri”. Ia sepenuhnya bergerak dalam kerangka ekonomi “Abenomi”, kombinasi dari kebijakan moneter ekspansif, peningkatan pengeluaran militer, dan nasionalisme.
Media lokal, karena gaya kepemimpinan dan fokus ekonominya yang keras, menjulukinya sebagai “Perempuan Besi baru” Asia Timur. Peniruan gaya ini menandakan kembalinya pada kebijakan ekonomi dan sosial yang otoriter, yang menurut para pengkritik berbahaya bagi masyarakat Jepang yang semakin beragam.
Ekonomi di ambang krisis dan meningkatnya ketidakpuasan
Jepang, yang selama beberapa dekade mengalami inflasi rendah, kini menghadapi kenaikan tajam harga dan penurunan daya beli. Kondisi ini memicu kemarahan publik dan ketidakpercayaan terhadap partai-partai tradisional, serta menciptakan ruang bagi pertumbuhan partai-partai sayap kanan.
Meskipun pasar saham Tokyo, sebagai reaksi terhadap program stimulus ekonomi Takaichi, naik ke titik tertinggi dalam sejarahnya, para ahli memperingatkan bahwa peningkatan utang publik — yang saat ini sudah berada di peringkat pertama di antara negara-negara industri — jika disertai dengan kebijakan mahal seperti perluasan anggaran militer dan subsidi energi, dapat berubah menjadi krisis yang tak terkendali.Kebangkitan kanan ekstrem dan kembalinya bayang-bayang nasionalisme
Naiknya Takaichi ke tampuk kekuasaan harus dianggap sebagai titik balik dalam pertumbuhan sayap kanan ekstrem di Jepang. Selain Partai Ishin, partai-partai ultra kanan seperti Sannseito juga telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru. Partai-partai ini, dengan slogan anti-imigrasi, anti-globalisasi, dan kembali pada “nilai-nilai asli”, tengah menarik lapisan masyarakat konservatif. Sikap Takaichi sendiri — mulai dari penolakannya terhadap pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak imigran hingga upayanya menulis ulang sejarah kejahatan perang Jepang dalam Perang Dunia II — semuanya menunjukkan kecenderungan berbahaya menuju nasionalisme ekstrem era pra-perang.
Menjadi perempuan tanpa feminisme; memperdalam kesenjangan gender
Meskipun media Barat menggambarkan naiknya Takaichi sebagai prestasi bagi perempuan, kenyataannya ia tidak pernah membela pandangan feminis. Takaichi menentang kuota gender dalam bidang politik dan manajemen, serta selalu membela “keluarga tradisional” dan “nilai-nilai berpusat pada keluarga”. Di negara yang perempuan-perempuannya menghadapi salah satu kesenjangan upah terbesar dan tingkat keterwakilan terendah dalam jabatan manajerial di antara negara maju, naiknya seorang perempuan dengan pandangan seperti itu — menurut banyak aktivis hak-hak perempuan — bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran besar.
Kesimpulan
Sanae Takaichi, meskipun mencatat sejarah sebagai perdana menteri perempuan pertama Jepang, kemungkinan besar akan dikenang bukan sebagai simbol kesetaraan, melainkan sebagai wajah dari gelombang baru otoritarianisme, nasionalisme, dan sayap kanan ekstrem.
Koalisi rapuhnya, meningkatnya pengaruh kelompok ultra kanan, tekadnya untuk melakukan militerisasi (peningkatan kekuatan militer), dan pelemahan layanan sosial — semuanya menunjukkan bahwa Jepang berada di ambang pergeseran historis ke arah kanan; pergeseran yang dapat menimbulkan tantangan serius terhadap perdamaian, stabilitas, dan demokrasi di negara itu serta di seluruh kawasan Asia Timur.